Literasi Media, Obat Mujarab Lenyapkan Virus Hoax
 |
| https://www.kreasitekno.com |
Indonesia
sebagai negara kepulauan (Archipelagic State) yang memiliki keaneka ragaman
baik dilihat dari segi ras, agama, bahasa, suku bangsa dan adat istiadat, serta kondisi faktual ini disatu sisi merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang
membedakannya dengan bangsa-bangsa lain yang tetap harus dipelihara.
Keanekaragaman tersebut juga mengandung potensi konflik yang jika tidak
dikelola dengan baik dapat mengancam keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa.
Kondisi ini dipengaruhi pula dengan menurunnya rasa nasionalisme yang ada
didalam masyarakat dan dapat berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan
yang akhirnya mengarah kepada disintegrasi bangsa, apabila tidak cepat
dilakukan tindakan-tindakan yang bijaksana untuk mencegah dan menanggulanginya
sampai pada akar permasalahannya secara tuntas maka akan menjadi problem yang
berkepanjangan. Ancaman global
yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia, salah satunya dengan
maraknya isu-isu berita hoax, fake news, berita fitnah dan berita
bohong yang tersebar luas melalui media sosial. Dibarengi dengan perkembangan teknologi digital yang penetrasinya cukup tinggi dan menjangkau hingga berbagai kalangan, maka peredaran informasi menjadi kian sulit terbendung. Namun, rupanya hal ini menimbulkan suatu polemik baru. Informasi benar dan salah menjadi campur aduk. Banyak netizen di Indonesia memiliki kecenderungan berlomba-lomba melemparkan isu dan ingin dianggap yang pertama. Hal ini nampak dalam pengiriman pesan melalui aplikasi WhatsApp, Facebook, Twitter, dan sebagainya.
Hoax adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk
mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu
bahwa berita tersebut adalah palsu. Salah satu contoh pemberitaan palsu
yang paling umum adalah mengklaim sesuatu barang atau kejadian dengan
suatu sebutan yang berbeda dengan barang/kejadian sejatinya. Dalam perkembangannya,
hoax sangat berpengaruh dalam memperdaya paradigma masyarakat dengan
bukti-bukti yang telah dipalsukan demi kepentingan pribadi ataupun kelompok.
Terutama dalam era digitalisasi ini berita hoax mudah sekali tersebar. Hal ini
dikarenakan wadah informasi sekarang ini tidak terbatas pada media seperti
televisi yang harus mendapatkan izin penayangan dari pemerintah melalui KPI
dalam setiap penyiaran beritanya, namun sekarang jauh lebih luas dan terbuka,
seperti mudahnya seseorang mengakses informasi dari internet, terutama media
sosial.
Kegaduhan
yang terjadi di media sosial semacam itu kerap kali menggunakan sentimen
identitas yang bermuara pada hujatan dan kebencian dan karenanya dapat
melunturkan semangat kemajemukan yang menjadi landasan masyarakat dalam
berbangsa. Pada akhirnya konsep tentang kebinekaan mengalami dekonstruksi oleh
argumen-argumen yang ikut dibentuk melalui media sosial. Di sisi lain,
persoalan mengatasi kegaduhan di media sosial melalui penegakan hukum juga
tidak perlu merusak semangat kebebasan berekspresi dalam sistem yang
demokratis. Hal ini didukung oleh
industri media itu sendiri dalam menyajikan format berita online yang kerap menyajikan informasi yang tidak utuh. Portal berita
yang paling banyak dibaca adalah yang memiliki kecenderungan menampilkan isi
(konten) berita yang hanya terdiri dari beberapa alinea, bahkan penyajiannya
cenderung tak lengkap dalam satu berita. Untuk mendapatkan informasi lengkap,
pembaca dipaksa untuk membaca lebih dari satu berita. Banyaknya persebaran hoax
bahkan dapat membuat kelompok terpelajar sekalipun tidak bisa membedakan
mana berita yang benar, advertorial dan hoax.
| http://detikfokus.com/ |
Dari sisi psikologis, orang lebih
cenderung percaya hoax jika informasinya sesuai dengan opini atau sikap yang
dimiliki. Secara alami perasaan positif akan timbul dalam diri seseorang jika
opini atau keyakinannya mendapat afirmasi sehingga cenderung tidak akan
mempedulikan apakah informasi yang diterimanya benar dan bahkan mudah saja bagi
mereka untuk menyebarkan kembali informasi tersebut. Hal ini dapat diperparah
jika si penyebar hoax memiliki pengetahuan yang kurang dalam memanfaatkan
internet guna mencari informasi lebih dalam atau sekadar untuk cek dan ricek
fakta.
Menurut riset yang
dilakukan Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) pada Februari 2017, Media
sosial adalah wadah paling favorid dalam penyebaran hoax, yaitu mencapai 92,4
persen. Media sosial yang dimaksud di sini termasuk Facebook, Twitter,
Instagram, Path, Line, WhatsApp, dan Telegram. Sedangkan menurut riset Mastel
tersebut penyebaran hoax melalui media lain relatif kecil, seperti situs web
(34,9 persen), televisi (8,7 persen), media cetak (5 persen), email (3,1
persen), dan radio (1,2 persen). Hal ini menunjukkan paradoks tersendiri
terhadap media sosial, dimana selain berfungsi untuk mempermudah akses
informasi dan komunikasi, ternyata juga dapat menimbulkan bencana dari mudahnya
penyebaran berita hoax di Indonesia. Pertemanan putus, keluarga tidak harmonis,
bahkan konflik horizontal sempat terjadi ketika ada sebagian warga yang
termakan oleh berita hoax.
Literasi yang sangat rendah di Indonesia ditengarahi turut pula berpengaruh terhadap kelonggaran mudahnya berita hoax diterima dan tersebar. Akibat minimnya literasi membuat seseorang kesulitan dalam menyeleksi berita yang benar karena tidak ada data yang bisa diperbandingkan dari bahan bacaan lain. Rendahnya literasi di Indonesia dibuktikan oleh data statistik UNESCO 2012 yang menyebutkan indeks minat baca di Indonesia baru mencapai 0,001. Artinya, setiap 1.000 penduduk, hanya satu orang saja yang memiliki minat baca. Jelas ini menjadi keprihatinan kita dalam budaya literasi bangsa tercinta.
Literasi yang sangat rendah di Indonesia ditengarahi turut pula berpengaruh terhadap kelonggaran mudahnya berita hoax diterima dan tersebar. Akibat minimnya literasi membuat seseorang kesulitan dalam menyeleksi berita yang benar karena tidak ada data yang bisa diperbandingkan dari bahan bacaan lain. Rendahnya literasi di Indonesia dibuktikan oleh data statistik UNESCO 2012 yang menyebutkan indeks minat baca di Indonesia baru mencapai 0,001. Artinya, setiap 1.000 penduduk, hanya satu orang saja yang memiliki minat baca. Jelas ini menjadi keprihatinan kita dalam budaya literasi bangsa tercinta.
Terbongkarnya Saracen
sebagai sindikat penyebar narasi kebencian konten hoax yang menggunakan isu SARA menjadi
bukti bahwa integrasi bangsa ini mempunyai ancaman serius. Sindikat jahat ini diduga mempunyai ratusan akun di media sosial Facebook. Modusnya, sindikat yang beraksi sejak
November 2015 tersebut mengirimkan proposal kepada sejumlah pihak, kemudian
menawarkan jasa penyebaran ujaran kebencian bernuansa SARA di media sosial.
Memang keliatan hanya bermotif uang semata, padahal dibalik itu adalah kejahatan luar biasa,
karena akan melibatkan semua anak bangsa untuk saling membenci dan saling
menyakiti. Kebutuhan politik untuk
meraih massa dilakukan dengan menciptakan kebencian terhadap orang atau kelompok
tertentu sehingga muncul pembelaan dan keberpihakan. Hal inilah yang
dimanfaatkan sebagai daya tarik bagi para pemodal politik untuk membeli jasa
dari sindikat Saracen. Cara-cara seperti, meskipun dengan dalih kepentingan
politik, sangat tidak terpuji dan keji, karena mengorbankan keutuhan bangsanya
sendiri demi kepetingan pribadi dan kelompoknya. Tindakan yang secara
sistematis melakukan aksi memecah belah warga negara merupakan kejahatan luar
biasa yang perlu dilakukan penanganan yang serius termasuk pihak yang membayar
dan mengendalikan Saracen wajib diusut tuntas.
Menyikapi semakin
masifnya berita-berita bohong (Hoax)
yang dapat menyebabkan perpecahan, membahayakan persatuan dan kesatuan,
kebhinnekaan tunggalikaan, dan munculnya kebencian diantara anak bangsa,
maka perlu upaya-upaya dari semua komponen masyarakat untuk
menyikapi media sosial dengan pembelajaran, kedewasaan, penuh kehati-hatian.
Berita bohong ini memang diciptakan untuk tujuan tertentu dengan memanfaatkan
media sosial yang begitu cepat sampai kepada masyarakat sebagai propaganda
kelompok tertentu untuk mempengaruhi pihak lain dengan tidak
mengindahkan etika, moral, aturan, nilai, norma dan lain-lain guna memenangkan
tujuan yang akan dicapai.
Dalam melawan hoax dan
mencegah meluasnya dampak negatif hoax, pemerintah pada dasarnya telah memiliki
payung hukum yang memadai. Pasal 28 ayat 1 dan 2 UU No. 11 tahun 2008 tentang
ITE, Pasal 14 dan 15 UU No. 1 tahun 1946, Pasal 311 dan 378 KUHP, serta UU No.
40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskiriminasi Ras dan Etnis merupakan
beberapa produk hukum yang dapat digunakan untuk memerangi penyebaran hoax.
Selain produk hukum, pemerintah juga sedang menggulirkan kembali wacana
pembentukan Badan Siber Nasional yang dapat menjadi garda terdepan dalam
melawan penyebaran informasi yang menyesatkan, selain memanfaatkan program
Internetsehat dan Trust+Positif yang selama ini menjalankan fungsi sensor dan
pemblokiran situs atau website yang ditengarai memiliki materi negatif yang
bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
Data yang dipaparkan oleh
Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan ada sebanyak 800 ribu situs
di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar berita palsu dan ujaran
kebencian (hate speech). Sepanjang
tahun 2016 Kominfo sudah memblokir 773 ribu situs berdasar pada 10 kelompok.
Kesepuluh kelompok tersebut di antaranya mengandung unsur pornografi, SARA,
penipuan/dagang ilegal, narkoba, perjudian, radikalisme, kekerasan, anak,
keamanan internet, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dari jumlah itu, paling
banyak yaitu unsur pornografi.
Meski demikian, persoalan persebaran informasi palsu atau hoax, tak hanya menjadi permasalahan di Tanah Air, tetapi menjadi isu global. Hal utama yang perlu diantisipasi sejak dini terkait dengan beredarnya berita bohong yaitu kebebasan setiap orang untuk mengeluarkan opini ke ranah publik. Kemampuan media sosial dalam menfasilitasi interaksi masyarakat dalam menanggapi sebuah berita yang tidak didasari oleh fakta dan tidak disusun berdasarkan prinsip jurnalistik berita akan menyebabkan terbentuknya opini publik yang merugikan semua pihak. Opini publik yang telah beredar di masyarakat akan menjadi lebih “liar” ketika terjadi polemik opini yang didasari oleh masing-masing masing-masing sudut pandang masyarakat. Polemik ini akan berpotensi meluas dan mampu menggerakkan masyarakat untuk membuktikan pandangannya, walaupun hal itu berisiko pada terjadinya konflik dalam masyarakat.
Dalam konteks semacam itu, kini pemerintah harus berfokus pada ‘hulu’ persebaran informasi palsu itu, dan bukan hanya melakukan pembatasan atau pemblokiran, melainkan lebih kepada mendidik masyarakat bagaimana mengembangkan literasi media yang baik. Beberapa waktu yang lalu juga mengemuka gagasan menerbitkan QR Code di setiap produk jurnalistik (berita dan artikel) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi validitas sebuah informasi. QR Code yang disertakan di setiap tulisan akan memuat informasi mengenai sumber berita, penulis, hingga perusahaan media yang menerbitkan tulisan tersebut sehingga suatu tulisan dapat dilacak hingga hulunya. Dengan demikian, kerukunan berbangsa masyarakat Indonesia dapat dipelihara sebaik mungkin.
Literasi media adalah perspektif yang dapat digunakan ketika berhubungan dengan media agar dapat menginterpretasikan suatu pesan yang disampaikan oleh pembuat berita. Orang cenderung membangun sebuah perspektif melalui struktur pengetahuan yang sudah terkonstruksi dalam kemampuan menggunakan informasi. Juga dalam pengertian lainnya yaitu kemampuan untuk mengevaluasi dan menkomunikasikan informasi dalam berbagai format termasuk tertulis maupun tidak tertulis. Literasi media digunakan sebagai model instruksional berbasis eksplorasi sehingga setiap individu dapat dengan lebih kritis menanggapi apa yang mereka lihat, dengar, dan baca. Tetapi kecakapan bermedia bukan hanya seputar persoalan mengonsumsi informasi. Kecakapan bermedia yang ideal dimaksudkan mengupayakan setiap individu mampu memproduksi, mengkreasi dan secara efektif berkomunikasi dalam berbagai wujud, tidak hanya cetak. Misalnya penggunaan teknologi internet untuk menghadirkan informasi yang memiliki konten yang lebih kaya dan menggapai sasaran yang lebih luas. Individu media setidaknya paham bahwa dengan internet mampu merepresentasikan kombinasi atas banyak wujud pesan, mulai dari pesan tertulis, video, suara, gambar dan animasi.
Meski demikian, persoalan persebaran informasi palsu atau hoax, tak hanya menjadi permasalahan di Tanah Air, tetapi menjadi isu global. Hal utama yang perlu diantisipasi sejak dini terkait dengan beredarnya berita bohong yaitu kebebasan setiap orang untuk mengeluarkan opini ke ranah publik. Kemampuan media sosial dalam menfasilitasi interaksi masyarakat dalam menanggapi sebuah berita yang tidak didasari oleh fakta dan tidak disusun berdasarkan prinsip jurnalistik berita akan menyebabkan terbentuknya opini publik yang merugikan semua pihak. Opini publik yang telah beredar di masyarakat akan menjadi lebih “liar” ketika terjadi polemik opini yang didasari oleh masing-masing masing-masing sudut pandang masyarakat. Polemik ini akan berpotensi meluas dan mampu menggerakkan masyarakat untuk membuktikan pandangannya, walaupun hal itu berisiko pada terjadinya konflik dalam masyarakat.
Dalam konteks semacam itu, kini pemerintah harus berfokus pada ‘hulu’ persebaran informasi palsu itu, dan bukan hanya melakukan pembatasan atau pemblokiran, melainkan lebih kepada mendidik masyarakat bagaimana mengembangkan literasi media yang baik. Beberapa waktu yang lalu juga mengemuka gagasan menerbitkan QR Code di setiap produk jurnalistik (berita dan artikel) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi validitas sebuah informasi. QR Code yang disertakan di setiap tulisan akan memuat informasi mengenai sumber berita, penulis, hingga perusahaan media yang menerbitkan tulisan tersebut sehingga suatu tulisan dapat dilacak hingga hulunya. Dengan demikian, kerukunan berbangsa masyarakat Indonesia dapat dipelihara sebaik mungkin.
Literasi media adalah perspektif yang dapat digunakan ketika berhubungan dengan media agar dapat menginterpretasikan suatu pesan yang disampaikan oleh pembuat berita. Orang cenderung membangun sebuah perspektif melalui struktur pengetahuan yang sudah terkonstruksi dalam kemampuan menggunakan informasi. Juga dalam pengertian lainnya yaitu kemampuan untuk mengevaluasi dan menkomunikasikan informasi dalam berbagai format termasuk tertulis maupun tidak tertulis. Literasi media digunakan sebagai model instruksional berbasis eksplorasi sehingga setiap individu dapat dengan lebih kritis menanggapi apa yang mereka lihat, dengar, dan baca. Tetapi kecakapan bermedia bukan hanya seputar persoalan mengonsumsi informasi. Kecakapan bermedia yang ideal dimaksudkan mengupayakan setiap individu mampu memproduksi, mengkreasi dan secara efektif berkomunikasi dalam berbagai wujud, tidak hanya cetak. Misalnya penggunaan teknologi internet untuk menghadirkan informasi yang memiliki konten yang lebih kaya dan menggapai sasaran yang lebih luas. Individu media setidaknya paham bahwa dengan internet mampu merepresentasikan kombinasi atas banyak wujud pesan, mulai dari pesan tertulis, video, suara, gambar dan animasi.
Di
Inggris dan Australia kecakapan bermedia seringkali menjadi mata pelajaran
tersendiri, sama halnya pada kurikulum Bahasa Inggris. Pada tingkatan senior,
usia 11 tahun dan 12 tahun, beberapa negara bagian menawarkan studi media
sebagai pilihan kajian. Misalnya banyak sekolah di Queensland menawarkan kajian
perfilman, televisi, dan media baru. Sedangkan
sekolah-sekolah di Victoria pendidikan media didukung penuh oleh asosiasi
guru-guru profesional yang mengajar subjek pelajaran media. Mereka tergabung
dalam Australian Teachers of Media (ATOM) yang juga menerbitkan sumber-sumber
penting berupa publikasi dan panduan yang baik.
Sementara itu di Eropa,
pendidikan media hadir dalam berbagai bentuk berbeda. Pendidikan media
diperkenalkan pada kurikulum dasar Finlandia pada tahun 1970 dan pada
pendidikan menengah atas di tahun 1977. Tetapi pendidikan media yang dikenal saat
ini tidak berkembang di Finlandia hingga tahun 1990-an. Sedangkan di Swedia
pendidikan media semakin berkembang sejak tahun 1980. Dan di Denmark sejak
tahun berkembang sejak tahun 1970 yang fokus pada teknologi informasi. Di
Prancis dan Jerman, masing-masing menitikberatkan pada film dan Jerman giat
menerbitkan teori-teori mengenai kecakapan bermedia.
Terkait
dengan literasi media ini,masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) menjabarkan beberapa langkah
yang bisa diterapkan pengguna internet
untuk mengetahui sebuah informasi layak dikonsumsi atau tidak. Dalam buku
panduan yang dirilis Mafindo setidaknya ada 5 cara yang patut diperhatikan
mengantisipasi kualitas informasi
1. Memeriksa ulang judul berita
provokatif. Judul berita kerap dipakai sebagai jendela untuk mengintip keseluruhan
tulisan. Namun tak jarang hal itu dimanfaatkan para penyebar berita palsu
dengan mendistorsi judul yang provokatif meski sama sekali tak relevan dengan
isi berita. Mafindo menyarankan pembaca untuk mengecek sumber berita lain agar
informasi yang diterima bukan hasil rekayasa.
2. Meneliti alamat situs web. Dewan Pers memiliki data
lengkap semua institusi pers resmi di Indonesia. Data yang terhimpun itu bisa
digunakan oleh pembaca sebagai referensi apakah sumber berita yang dibaca telah
memenuhi kaidah jurnalistik sesuai aturan Dewan Pers. Cukup mengetik nama situs
berita di kolom data pers, pembaca dapat mengetahui status media yang mereka
konsumsi berdasarkan standar Dewan Pers.
3. Membedakan fakta dengan opini. Mafindo menganjurkan
pembaca tidak menelan mentah-mentah ucapan seorang narasumber yang dikutip oleh
situs berita. Sering kali hal itu luput dari pembaca karena pembaca terlalu
cepat mengambil kesimpulan. Semakin banyak fakta yang termuat di sebuah berita,
makin banyak kredibel berita itu.
4. Cermat membaca korelasi foto dan caption yang provokatif.
Persebaran foto provokatif dengan imbuhan tulisan yang telah disunting. Cara
termudah menguji keabsahan informasi dari foto yang diterima, pembaca bisa
membuka Google Images di aplikasi penjelajah lalu menyeret foto yang dimaksud
ke kolom pencarian.
5. Ikut serta dalam komunitas daring. Menurut
Mafindo, setidaknya ada empat komunitas yang getol memerangi berita palsu di
Indonesia. Keempatnya itulah yang menjelma menjadi Mafindo. Dengan model crowdsourcing, komunitas
itu berusaha menyaring dan mengklarifikasi informasi yang meragukan
kebenarannya.
| http://tribratanews.kepri.polri.go.id |
Salah satu tantangan rakyat Indonesia
saat ini adalah bagaimana menjadikan multikulturalisme itu sebagai kekuatan,
yang tentunya nanti bisa membawa rakyat pada persatuan dan kesatuan bangsa.
Multikulturalisme masyarakat Indonesia dapat menimbulkan masalah tentang
sulitnya membangun masyarakat Indonesia yang terintegrasi pada tingkat lokal
dan tingkat nasional. Salah satu masalah yang ada dalam masyarakat terkait
multikulturalisme adalah konflik yang dapat memecah persatuan dan kesatuan
dalam masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan strategi pemerintah untuk
menghindari perpecahan akibat dampak negatif multikulturalisme.
Sejalan dengan pemikiran Prof.Din Syamsudin selaku Presiden Komite Keagamaan dan Perdamaian Asia, bahwa untuk membangun persatuan melalui multikulturalisme, pertama, harus ada kesadaran tentang pentingnya multikulturalisme, yang dalam pandangan Islam adalah hukum (ketetapan) Tuhan, dan kedua, mengembangkan budaya dalam masyarakat untuk saling menghargai dan tenggang rasa. Memang ada perbedaan di antara kelompok masyarakat, tetapi di sisi lain, juga ada persamaan, oleh karena itu penting mencari titik temunya. Indonesia sangat beruntung karena pendiri bangsa ini telah mewariskan dua pedoman yang bisa menyatukan kemajemukan dalam masyarakat, yakni Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Perlu semangat kebersamaan, kerjasama, dan berbagi atas nama kemanusiaan tanpa memandang perbedaan untuk menguatkan persatuan di antara masyarakat dengan budaya yang beragam. Sikap saling menghormati identitas masing-masing dan kesediaan untuk tidak memaksakan pandangan sendiri tentang “yang baik” kepada siapapun merupakan syarat keberhasilan masa depan Indonesia. Untuk itu, diperlukan transformasi kesadaran multikulturalisme menjadi identitas nasional, integrasi nasional, dan menempatkan agama menjadi fondasi kesatuan bangsa.
Referensi :
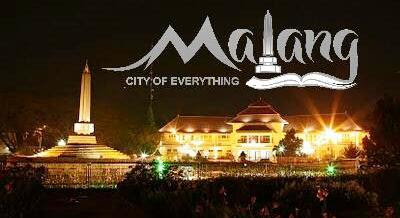





Leave a Comment